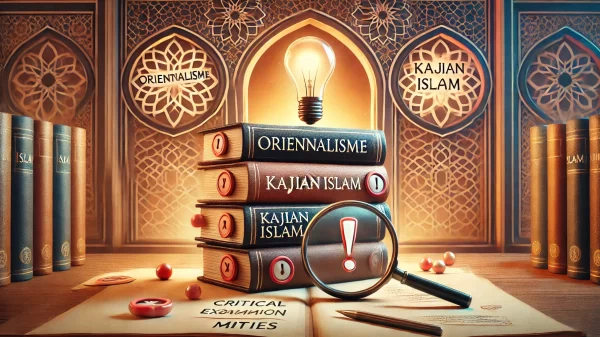Monitorday com – Dalam sejarah spiritualitas Islam, zuhud selalu menjadi sikap yang dimuliakan. Ia bukan sekadar praktik menjauhi dunia, tetapi sebuah kesadaran mendalam bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Di era digital yang serba cepat dan penuh godaan ini, zuhud bukan kehilangan makna, justru semakin relevan untuk menjaga kebeningan hati dan keteguhan iman.
Zuhud secara sederhana dapat dimaknai sebagai sikap tidak tergantung pada dunia, meskipun seseorang memilikinya. Bukan berarti seseorang harus meninggalkan harta, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Zuhud bukan kemiskinan, tetapi kebebasan batin. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, “Zuhud itu bukan berarti kamu tidak memiliki apa-apa, tetapi kamu tidak diperbudak oleh apa yang kamu miliki.”
Kini, kita hidup di tengah kemewahan digital: gawai canggih, media sosial, aplikasi yang memanjakan, hingga budaya viral yang serba instan. Kita terhubung dengan dunia dalam sekejap, namun seringkali menjadi hamba dari layar yang ada di genggaman. Ketergantungan ini membuat zuhud terasa jauh dari kehidupan modern, padahal justru dibutuhkan lebih dari sebelumnya.
Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah overstimulation—banjir informasi, notifikasi tanpa henti, dan dorongan untuk selalu terlihat eksis. Inilah bentuk perbudakan modern yang halus: kita merasa harus terus merespon, terus mengikuti tren, terus membandingkan hidup dengan orang lain. Dalam situasi ini, zuhud hadir sebagai jalan pembebasan. Ia mengajak kita melepaskan keterikatan, bukan benda fisik semata, tapi juga ikatan mental terhadap pengakuan, validasi, dan pencitraan.
Zuhud di era ini bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil: membatasi waktu layar, mengurangi konsumsi media sosial, atau memilih untuk tidak mengikuti tren yang tak bermanfaat. Hal ini bukan berarti menolak teknologi, tapi menggunakannya dengan bijak. Dalam pandangan seorang zahid, teknologi adalah alat, bukan tujuan. Ia tidak membiarkan hidupnya dikendalikan oleh algoritma, melainkan tetap menjaga ruh dan arah hidupnya dengan sadar.
Para ulama dahulu memberi contoh tentang bagaimana memiliki dunia tapi tidak mencintainya secara berlebihan. Umar bin Khattab, meski seorang pemimpin besar, tetap hidup sederhana dan tidak terikat pada kekayaan duniawi. Begitu pula Imam Hasan al-Bashri yang sangat meyakini bahwa ketenangan hanya didapat ketika hati tidak bergantung pada dunia. Dalam konteks hari ini, kita bisa meneladani mereka dengan cara menjadi pengguna teknologi yang beretika, tidak silau dengan gaya hidup digital yang penuh glamor, dan tetap menjadikan akhirat sebagai orientasi utama.
Menjadi zahid di era digital juga berarti mampu mengatakan “cukup” ketika dunia terus menawarkan “lebih”. Kita tidak harus selalu memiliki gadget terbaru, mengikuti gaya hidup influencer, atau merasa tertinggal saat tidak mengonsumsi hal-hal viral. Zuhud menanamkan rasa qana’ah—merasa cukup dengan yang ada. Dengan itu, hati menjadi tenang, dan hidup lebih fokus.
Lebih dari itu, zuhud melatih kita untuk hidup dengan kesadaran. Setiap interaksi digital seharusnya menjadi ladang amal, bukan ladang kesia-siaan. Kita bisa bertanya pada diri: apakah waktu yang saya habiskan di media sosial mendekatkan saya pada Allah? Apakah unggahan saya membawa manfaat atau sekadar pamer? Apakah saya menjadi hamba Allah, atau hamba dari likes dan komentar?
Dalam perspektif sufistik, zuhud adalah langkah awal menuju ma’rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tanpa melepaskan diri dari keterikatan dunia, hati sulit menerima cahaya ilahi. Maka, siapa yang ingin naik derajat spiritual, ia harus rela membersihkan hatinya dari cinta dunia. Di zaman sekarang, cinta dunia itu bisa berbentuk obsesi pada popularitas digital, pencapaian semu, atau kemewahan virtual yang hanya tampak di layar.
Zuhud bukan pelarian dari kehidupan, tapi cara hidup yang jernih. Seorang zahid tetap bekerja, tetap bersosialisasi, bahkan bisa sukses di dunia, tapi hatinya tidak pernah tergantung padanya. Ia tidak sedih saat kehilangan, dan tidak bangga berlebihan saat mendapatkannya. Dunia ada di tangannya, bukan di hatinya.
Maka, menjadi zahid di era digital adalah perjuangan untuk tetap merdeka—merdeka dari keinginan tanpa batas, merdeka dari pencitraan, dan merdeka dari tekanan eksistensi virtual. Merdeka untuk memilih hidup yang bermakna, bukan yang sekadar terlihat menakjubkan di layar. Inilah esensi zuhud yang abadi: menjadikan dunia sebagai jembatan, bukan jebakan.
Zuhud di era digital memang tidak mudah. Tapi ia sangat mungkin, dan sangat dibutuhkan. Ia adalah benteng di tengah banjir informasi. Ia adalah oase di tengah hiruk-pikuk pencitraan. Dan yang terpenting, ia adalah jalan menuju kebebasan sejati—bebas dari dunia yang memperbudak, dan bebas untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih.