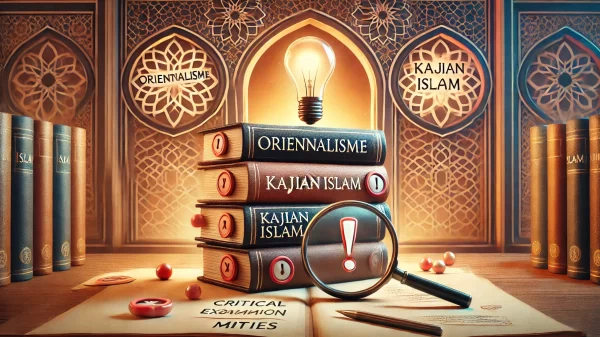Abu al-Abbas as-Saffah bukan hanya dikenal sebagai pendiri Dinasti Abbasiyah, tetapi juga sebagai pembuka jalan bagi lahirnya era keemasan peradaban Islam. Meski masa pemerintahannya singkat — hanya empat tahun (132–136 H / 750–754 M) — kebijakan, visi, dan arah baru yang ia tanamkan menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya kekhalifahan yang akan memimpin dunia Islam selama lebih dari lima abad. Di tangannya, dan terutama di tangan para penerusnya, Islam memasuki masa yang gemilang dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
Warisan pertama dan terpenting dari Abu al-Abbas adalah pergeseran orientasi peradaban Islam dari barat ke timur. Jika Dinasti Umayyah sebelumnya berpusat di Damaskus (Suriah modern) dan berfokus pada ekspansi militer, maka Abbasiyah mengalihkan pusat kekuasaan ke wilayah Irak dan Persia, yang menjadi jantung intelektual dan ekonomi dunia saat itu. Abu al-Abbas menjadikan Kufah sebagai ibu kota sementara, kemudian mempersiapkan pembangunan kota baru yang kelak menjadi simbol kejayaan Islam: Baghdad.
Pemindahan pusat pemerintahan ini bukan hanya keputusan geografis, tetapi juga pergeseran paradigma peradaban. Di bawah Abbasiyah, Islam menjadi lebih terbuka terhadap berbagai bangsa dan budaya. Orang-orang Persia, Turki, dan bahkan non-Muslim seperti Yahudi dan Nasrani diberi ruang untuk berkontribusi dalam bidang ilmu, pemerintahan, dan ekonomi. Ide besar Abu al-Abbas adalah membangun kekhalifahan yang bersandar pada ilmu pengetahuan dan keadilan sosial, bukan sekadar kekuatan militer.
Warisan kedua adalah penghapusan diskriminasi sosial dan etnis yang selama ini membayangi masa Umayyah. Abu al-Abbas memerintahkan agar kaum mawali (Muslim non-Arab) diperlakukan setara dengan Muslim Arab dalam pajak, hukum, dan jabatan pemerintahan. Langkah ini membawa dampak besar: umat Islam di berbagai penjuru dunia merasa memiliki rumah baru di bawah panji Abbasiyah. Kesetaraan ini menjadi salah satu faktor penting yang memperkuat loyalitas rakyat terhadap kekhalifahan baru.
Warisan ketiga adalah pembangunan sistem administrasi dan keuangan yang terorganisir. Abu al-Abbas menata ulang Baitul Mal (kas negara) dan memperkenalkan sistem pencatatan keuangan yang lebih modern. Ia memerintahkan agar pajak dikelola dengan adil dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum — pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Ia juga menekan praktik korupsi yang marak di masa akhir Umayyah, menggantinya dengan sistem pengawasan yang ketat melalui pejabat-pejabat yang dipilih berdasarkan loyalitas dan kemampuan, bukan garis keturunan.
Warisan keempat adalah penguatan peran ilmu dan ulama dalam pemerintahan. Meskipun sibuk mengonsolidasikan kekuasaan, Abu al-Abbas sudah mulai menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan keilmuan. Ia memberi dukungan kepada para ahli fikih, ahli hadis, dan penulis yang aktif di Kufah dan Basrah. Ia juga mengizinkan berdirinya halaqah-halaqah ilmu di masjid-masjid besar, tempat para ulama berdiskusi dan mengajarkan tafsir, hukum, serta bahasa Arab. Dari pondasi inilah, pada masa penerusnya seperti Abu Ja’far al-Mansur dan Harun ar-Rasyid, lahir Baitul Hikmah (House of Wisdom) — lembaga penerjemahan dan riset yang menjadikan Baghdad pusat ilmu pengetahuan dunia.
Selain bidang ilmu dan pemerintahan, Abu al-Abbas juga meninggalkan citra moral dan religius baru dalam kepemimpinan Islam. Ia menampilkan diri sebagai pemimpin umat, bukan sekadar raja. Dalam khutbah dan pernyataannya, ia sering menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak turun-temurun. Ia berkata, “Kami tidak berperang untuk dunia, tetapi untuk menegakkan keadilan di muka bumi.” Prinsip ini menjadi ciri khas pemerintahan Abbasiyah yang menempatkan moralitas dan ilmu sebagai dua pilar utama.
Meskipun mendapat julukan as-Saffah (“penumpah darah”) karena kekerasannya terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah, sejarah menilai bahwa kebijakan tegas itu justru menyelamatkan kekhalifahan baru dari perang saudara. Tanpa langkah keras itu, mungkin Dinasti Abbasiyah tidak akan pernah berdiri kokoh. Setelah keamanan dan stabilitas tercapai, ia justru membuka ruang bagi pembangunan, integrasi sosial, dan kemajuan intelektual.
Ketika Abu al-Abbas wafat pada tahun 136 H (754 M), kekhalifahan Abbasiyah telah berdiri tegak dengan struktur pemerintahan yang stabil. Ia digantikan oleh pamannya, Abu Ja’far al-Mansur, yang melanjutkan proyek besar membangun Baghdad dan mengokohkan fondasi peradaban Islam. Karena itulah, banyak sejarawan menyebut Abu al-Abbas sebagai “batu pertama dari bangunan peradaban Abbasiyah.”
Warisan Abu al-Abbas as-Saffah tidak hanya berupa dinasti baru, tetapi juga gagasan besar tentang pemerintahan Islam yang berbasis ilmu dan keadilan. Ia membuka jalan bagi lahirnya zaman keemasan Islam — masa di mana Baghdad menjadi pusat dunia, tempat para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Al-Kindi menulis karya yang kelak memengaruhi seluruh peradaban manusia.
Dengan demikian, meskipun pemerintahannya singkat dan diwarnai darah, jejak Abu al-Abbas abadi dalam sejarah Islam. Ia menutup bab konflik lama dan membuka era baru di mana pena dan ilmu pengetahuan menjadi senjata utama umat Islam. Dari tangannya, Islam tidak hanya berjaya di medan perang, tetapi juga di medan akal dan peradaban.