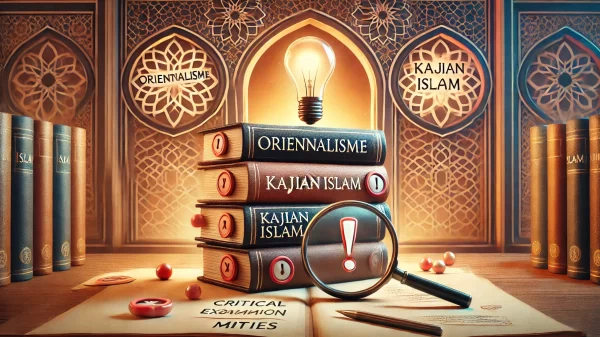Monitorday.com – Tahun 813 Masehi atau 198 Hijriah tercatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu masa paling kelam bagi Dinasti Abbasiyah. Di tahun inilah, Baghdad — kota ilmu, pusat kebudayaan, dan simbol kejayaan Islam — berubah menjadi medan perang dan lautan darah. Konflik saudara antara Khalifah Al-Amin dan saudaranya Al-Ma’mun mencapai puncaknya, menghancurkan bukan hanya istana, tapi juga fondasi moral dan spiritual yang dibangun oleh ayah mereka, Harun ar-Rasyid.
Selama hampir setahun, Baghdad dikepung oleh pasukan Khurasan di bawah komando jenderal ulung, Tahir bin Husain, yang memimpin tentara atas nama Al-Ma’mun. Pengepungan ini dimulai pada awal tahun 197 H (812 M) dan menjadi salah satu perang kota paling brutal dalam sejarah dunia Islam.
Sebelum pengepungan, Baghdad masih tampak sebagai kota yang makmur. Pasar-pasar ramai, masjid-masjid penuh jamaah, dan perpustakaan masih hidup dengan kegiatan ilmiah. Namun semua berubah ketika pasukan Khurasan mulai menutup jalur perdagangan dan memblokir Sungai Tigris, nadi ekonomi kota itu. Jalur air yang biasanya mengantarkan makanan, obat, dan bahan kebutuhan kini menjadi ladang pertempuran.
Pasukan Al-Amin, meskipun lebih banyak jumlahnya, tidak memiliki koordinasi yang baik. Banyak tentara bayaran yang akhirnya membelot karena gaji tak dibayar. Sebaliknya, pasukan Tahir bin Husain terlatih dan disiplin. Mereka menguasai strategi militer dan didukung penuh oleh Al-Ma’mun di Khurasan.
Ketika musim panas tiba, bencana kelaparan melanda Baghdad. Harga gandum naik seratus kali lipat. Rakyat mulai memakan dedaunan, kulit pohon, bahkan bangkai binatang. Sungai Tigris yang dulu menjadi sumber kehidupan kini dipenuhi mayat tentara dan warga sipil. Setiap hari, ratusan jenazah dikuburkan tanpa nama. Sejarawan Al-Tabari menulis, “Bau kematian memenuhi udara Baghdad, dan cahaya ilmu pun padam di tengah jeritan rakyat yang lapar.”
Meskipun situasi memburuk, Al-Amin tetap menolak menyerah. Ia berpegang pada kehormatan dan warisan ayahnya sebagai khalifah sah Abbasiyah. Ia memerintahkan rakyat untuk tetap berjuang dan menyemangati mereka dengan kata-kata:
> “Lebih baik mati dengan martabat daripada hidup dalam hina.”
Namun waktu tidak berpihak padanya. Pasukan Tahir berhasil menembus tembok kota Baghdad melalui jembatan Tigris yang rusak. Pertempuran sengit terjadi dari rumah ke rumah. Istana Al-Amin yang megah di Qasr al-Khuld dibakar, dan sebagian besar keluarga kerajaan tewas atau ditangkap.
Pada malam yang sunyi di bulan Muharram tahun 198 H, Al-Amin berusaha melarikan diri dengan perahu kecil menyusuri Sungai Tigris, membawa serta pusaka kekhalifahan: pedang, stempel, dan bendera hitam Abbasiyah. Namun ia dikhianati oleh beberapa pengawal yang menyerah kepada pasukan Khurasan.
Al-Amin ditangkap dan dibawa ke hadapan komandan musuh. Menurut catatan sejarah, ia sempat memohon agar nyawanya diselamatkan dengan syarat menyerahkan kekuasaan. Tetapi Tahir bin Husain, yang mendapat perintah tegas dari Al-Ma’mun, menolak tawaran itu. Dalam malam gelap tanpa saksi, Al-Amin dieksekusi di usia 27 tahun. Kepalanya dikirim ke Khurasan sebagai bukti kemenangan.
Kematian Al-Amin mengguncang dunia Islam. Rakyat Baghdad menangis bukan hanya karena kehilangan khalifah, tetapi karena kehancuran moral dan spiritual yang menyertai perang ini. Masjid-masjid sepi, pasar hancur, dan api masih menyala di reruntuhan istana. Kota yang dulu dijuluki “Baghdad al-Zahra” — Baghdad yang bercahaya — kini berubah menjadi puing dan abu.
Namun dari kehancuran ini, muncul juga babak baru. Setelah perang usai, Al-Ma’mun naik sebagai khalifah tunggal. Ia memulihkan Baghdad secara perlahan, memperbaiki sistem pemerintahan, dan mengembalikan peran ilmu pengetahuan. Namun trauma perang saudara itu tak pernah benar-benar hilang. Banyak ulama menilai bahwa masa kejayaan Abbasiyah mulai retak sejak tragedi itu.
Sejarawan Ibn Khaldun menyebut peristiwa ini sebagai “titik balik yang memisahkan antara kemakmuran dan kemunduran.” Sementara Al-Tabari menulis dengan getir, “Kekuasaan telah menghapus kasih di antara dua darah yang sama.”
Tragedi Baghdad tahun 813 M bukan sekadar perang dua saudara, tapi simbol kehancuran peradaban akibat ambisi manusia. Ia mengingatkan bahwa peradaban besar bisa runtuh bukan karena serangan luar, tetapi karena perpecahan di dalam tubuhnya sendiri.
Dari puing-puing itu, lahirlah pelajaran abadi: bahwa kejayaan sejati tidak terletak pada istana yang tinggi atau pasukan yang kuat, melainkan pada persatuan dan keadilan.
Ketika api padam dan Baghdad kembali sunyi, dunia Islam kehilangan satu cahaya besar. Tapi dari gelapnya malam itu, lahirlah babak baru — masa Al-Ma’mun, khalifah yang akan membangun kembali kejayaan Abbasiyah melalui ilmu, akal, dan kebijaksanaan.