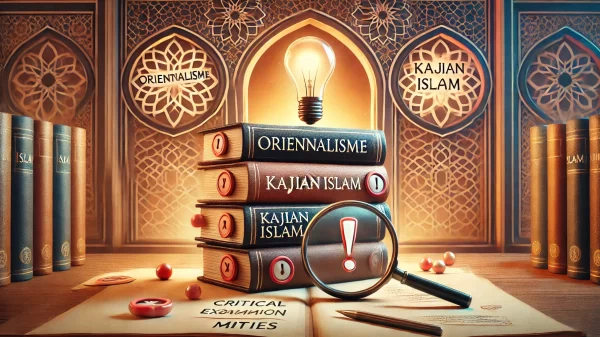Abu Ja’far al-Mansur bukan sekadar khalifah kedua Dinasti Abbasiyah; ia adalah arsitek sejati dari kejayaan Islam klasik. Dengan ketegasan, kecerdasan politik, dan visi peradaban yang tajam, ia mengubah kekhalifahan muda yang baru lahir menjadi negara yang stabil, berilmu, dan berwibawa. Warisan al-Mansur melampaui batas zamannya — ia membangun fondasi yang kokoh bagi masa keemasan Islam yang berlangsung selama berabad-abad setelahnya.
Warisan pertama yang paling berharga dari Abu Ja’far adalah stabilitas politik dan pemerintahan yang teratur. Saat ia naik tahta, dunia Islam baru saja keluar dari revolusi Abbasiyah yang berdarah. Banyak wilayah masih bergejolak, dan pengaruh Umayyah belum sepenuhnya lenyap. Dengan ketegasan luar biasa, al-Mansur menata ulang seluruh struktur pemerintahan. Ia memperkuat kekuasaan pusat di Baghdad, menertibkan birokrasi, dan menegakkan sistem pengawasan terhadap pejabat negara. Di bawahnya, setiap gubernur, hakim, dan bendahara diwajibkan melapor langsung ke khalifah melalui sistem barid (pos intelijen). Hal ini memastikan bahwa negara berjalan efisien dan bebas dari penyimpangan.
Selain kekuatan politik, al-Mansur juga meninggalkan warisan besar dalam bidang keadilan dan moral pemerintahan. Ia dikenal sangat hati-hati dalam mengeluarkan keputusan hukum dan selalu meminta nasihat para ulama. Dalam banyak riwayat, ia disebut sering meminta pendapat Imam Malik bin Anas tentang hukum syariah, bahkan berniat menjadikan kitab Al-Muwaththa’ sebagai hukum resmi negara. Meskipun rencana itu tidak terealisasi, kebijakannya menunjukkan betapa besar penghormatannya terhadap ilmu dan keadilan.
Al-Mansur memandang keadilan sebagai pondasi utama kekuasaan. Ia pernah berkata, “Keadilan adalah tiang kekuasaan; jika ia runtuh, maka runtuhlah negara.” Karena itu, ia memperlakukan rakyatnya dengan penuh tanggung jawab. Ia menolak hidup mewah, mengawasi langsung kas negara, dan sering turun menyamar untuk melihat keadaan rakyat di Baghdad. Ia ingin memastikan bahwa pemerintahannya benar-benar membawa kemaslahatan, bukan kesengsaraan.
Warisan ketiga yang monumental adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di masa al-Mansur, benih intelektual yang kelak tumbuh menjadi peradaban besar mulai disemai. Ia mendorong penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, terutama di bidang kedokteran, astronomi, dan matematika. Para ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai bangsa diundang ke Baghdad. Dari sinilah lahir tradisi ilmiah yang kemudian berkembang di masa Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun dengan berdirinya Baitul Hikmah (House of Wisdom).
Kebijakan ini menjadikan Baghdad bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi pusat ilmu pengetahuan dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa universal sains dan filsafat, menggantikan Yunani dan Latin. Tradisi rasional Islam tumbuh pesat, dan dari warisan inilah kelak lahir ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Biruni. Semua itu berakar dari visi al-Mansur yang melihat bahwa kekuatan umat Islam tidak hanya pada pedang, tetapi juga pada pena.
Warisan keempat adalah pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Al-Mansur mengelola Baitul Mal dengan ketat, menekan pengeluaran istana, dan mengutamakan pembangunan infrastruktur. Ia memperluas jalur perdagangan antara Timur dan Barat, memperbaiki jalan-jalan menuju Basrah dan Syam, serta memperkuat pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia. Ia juga menata ulang sistem pajak agar adil dan tidak membebani rakyat. Berkat kebijakan ini, kekhalifahan Abbasiyah menjadi salah satu negara terkaya dan paling berpengaruh di dunia pada abad ke-8.
Warisan kelima — dan mungkin yang paling monumental — adalah kota Baghdad itu sendiri. Dibangun pada tahun 762 M, kota ini bukan hanya ibu kota administratif, tetapi simbol peradaban Islam. Ia dirancang melingkar sempurna, dengan istana khalifah di pusatnya dan masjid agung sebagai poros spiritualnya. Di bawah al-Mansur, Baghdad tumbuh menjadi kota kosmopolitan dengan pasar yang ramai, perpustakaan yang megah, dan masyarakat multikultural yang hidup berdampingan dalam damai. Kota ini menjadi model bagi kota-kota besar dunia selanjutnya.
Dari sisi pribadi, Abu Ja’far al-Mansur juga meninggalkan keteladanan kepemimpinan. Ia dikenal tegas namun adil, cerdas namun sederhana. Ia tidur di tempat sederhana, makan apa adanya, dan menolak hadiah berlebihan dari pejabat. Ia tidak hanya memimpin dengan perintah, tetapi juga dengan contoh. Ia menjadikan pemerintahan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, bukan alat mencari kemuliaan dunia.
Ketika wafat dalam perjalanan haji ke Makkah pada tahun 158 H (775 M), Abu Ja’far meninggalkan dunia dengan nama harum dan pemerintahan yang stabil. Ia digantikan oleh putranya, Al-Mahdi, yang melanjutkan kebijakan ayahnya dan membawa kekhalifahan menuju puncak kejayaan spiritual dan intelektual.
Warisan Abu Ja’far al-Mansur tidak dapat diukur hanya dengan bangunan dan kebijakan, tetapi dengan roh peradaban yang ia bangkitkan. Ia menanamkan prinsip bahwa kekuasaan tanpa keadilan adalah kezaliman, dan ilmu tanpa iman adalah kesia-siaan. Melalui visi dan kebijaksanaannya, ia membentuk wajah Islam sebagai peradaban besar yang mencintai pengetahuan, menghormati moralitas, dan menjunjung tinggi keadilan.
Dari tangannya, dunia Islam tidak hanya berdiri tegak, tetapi bersinar — menjadi mercusuar bagi dunia. Dan dari warisannya, umat Islam belajar bahwa peradaban sejati dibangun bukan oleh kekuatan, melainkan oleh nilai dan pengetahuan.