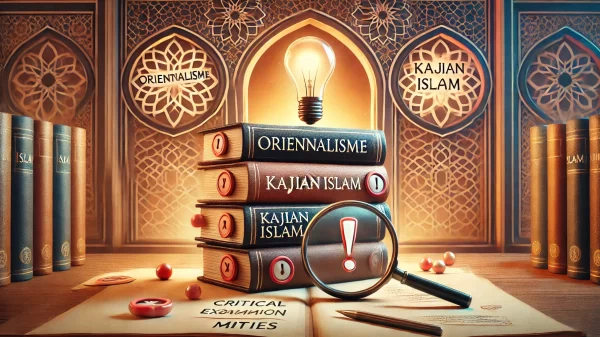Ketika Abu Ja’far al-Mansur memutuskan untuk membangun ibu kota baru di tepi Sungai Tigris, banyak orang belum menyadari bahwa keputusan itu akan mengubah arah sejarah dunia. Kota itu kelak dikenal sebagai Baghdad — bukan sekadar pusat pemerintahan, tetapi jantung peradaban Islam dan simbol keemasan intelektual umat. Di bawah kepemimpinan al-Mansur (136–158 H / 754–775 M), Baghdad tumbuh menjadi kota termakmur, terindah, dan paling berpengaruh di dunia abad pertengahan.
Al-Mansur mendirikan Baghdad pada tahun 145 H (762 M) dengan visi yang luar biasa jauh ke depan. Ia ingin membangun kota yang tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik Abbasiyah, tetapi juga pusat ilmu, ekonomi, dan spiritualitas Islam. Letaknya dipilih dengan sangat strategis — di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat, yang menjadi jalur perdagangan utama antara Timur dan Barat. Posisi ini menjadikan Baghdad pusat konektivitas antara Persia, India, dan dunia Mediterania.
Kota itu dirancang dengan arsitektur yang revolusioner. Abu Ja’far sendiri ikut menentukan desainnya. Ia memilih bentuk lingkaran sempurna, melambangkan keseimbangan dan keteraturan kekuasaan. Di tengahnya berdiri Jami’ al-Mansur (Masjid Agung) dan Qasr al-Khilafah (Istana Khalifah), dikelilingi oleh tembok tinggi dan empat gerbang megah: Bab al-Kufah, Bab al-Basrah, Bab al-Khurasan, dan Bab asy-Syam. Dari setiap gerbang, jalan utama mengarah langsung ke pusat kota, tempat khalifah memimpin pemerintahan.
Desain kota ini bukan hanya estetika, tetapi juga simbol filosofi pemerintahan al-Mansur: bahwa khalifah adalah pusat keadilan dan ilmu, dan segala urusan negara berputar di sekitarnya dengan keteraturan yang sempurna. Pembangunan kota ini memakan waktu empat tahun dan melibatkan lebih dari 100.000 pekerja, arsitek, dan insinyur dari Persia, Suriah, dan Mesir.
Begitu selesai, Baghdad segera menjadi pusat kekuasaan Islam yang tak tertandingi. Administrasi negara dijalankan dengan sangat efisien dari sini. Para gubernur, pejabat, dan ulama dari berbagai provinsi datang ke Baghdad untuk melapor atau menimba ilmu. Jalan-jalan besar membentang menuju pasar-pasar yang ramai, sementara sungai Tigris dipenuhi kapal dagang dari India, Cina, dan Afrika Timur. Di setiap sudutnya, kehidupan berdenyut dalam keseimbangan antara spiritualitas dan kemajuan.
Namun, keagungan Baghdad tidak hanya terletak pada bangunannya, tetapi juga pada jiwa intelektual yang tumbuh di dalamnya. Al-Mansur membuka pintu kota bagi para ulama, cendekiawan, dan penerjemah dari berbagai bangsa. Ia mengundang ilmuwan Persia dan Yunani untuk menerjemahkan karya-karya mereka ke dalam bahasa Arab. Di sinilah benih awal dari lembaga legendaris Baitul Hikmah (House of Wisdom) mulai tumbuh — pusat penerjemahan dan penelitian yang kelak menjadi mercusuar ilmu pengetahuan dunia Islam.
Kebijakan al-Mansur yang mendorong ilmu dan pendidikan menjadikan Baghdad sebagai magnet bagi para ilmuwan dan pemikir besar. Di masa ini, muncul tokoh-tokoh seperti Imam Malik bin Anas di Madinah dan Imam Abu Hanifah di Kufah, yang keduanya mendapat perhatian besar dari khalifah. Meskipun sempat berselisih pandangan politik, al-Mansur tetap menghormati mereka sebagai ulama besar dan menjadikan karya-karya mereka sebagai rujukan hukum Islam.
Selain ilmu, ekonomi Baghdad berkembang pesat di bawah al-Mansur. Pasar-pasar besar seperti Suq al-Karkh dan Suq al-Mansur menjual barang-barang dari tiga benua: sutra dari Cina, rempah dari India, emas dari Afrika, dan kain halus dari Andalusia. Sistem perpajakan yang tertata rapi memastikan kesejahteraan rakyat tanpa memberatkan mereka. Kas negara penuh, tetapi al-Mansur tetap hidup sederhana, menolak kemewahan istana, dan sering berkata, “Kekayaan negara bukan milik khalifah, melainkan amanah Allah bagi rakyat.”
Dari sisi sosial, Baghdad menjadi kota yang multikultural dan toleran. Orang Arab, Persia, Turki, Kurdi, Yahudi, dan Nasrani hidup berdampingan dalam suasana damai. Mereka bekerja, berdagang, dan belajar bersama. Hal ini menjadikan Baghdad bukan hanya kota Islam, tetapi kota dunia. Ia menjadi laboratorium sosial di mana nilai Islam — keadilan, ilmu, dan kemanusiaan — diwujudkan dalam kehidupan nyata.
Kota ini juga menjadi simbol kemajuan teknologi dan arsitektur. Jembatan-jembatan besar melintasi Sungai Tigris, air dialirkan ke taman-taman dan rumah-rumah, dan lampu-lampu minyak menerangi jalan-jalan di malam hari. Bahkan menurut catatan sejarah, Baghdad menjadi kota pertama di dunia yang memiliki sistem pos, rumah sakit, dan lembaga penerjemahan yang terorganisir secara resmi oleh negara.
Di masa akhir hayatnya, Abu Ja’far al-Mansur menyaksikan bagaimana kota yang ia rancang telah berubah menjadi permata Islam. Ia wafat pada tahun 158 H (775 M) dalam perjalanan haji, meninggalkan Baghdad sebagai warisan terbesarnya — kota yang bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga pusat ilmu, sastra, dan peradaban.
Baghdad di bawah al-Mansur bukan hanya ibu kota kekhalifahan; ia adalah simbol kejayaan intelektual dan spiritual Islam. Di sinilah lahir generasi cendekiawan yang akan melahirkan penemuan-penemuan besar dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Di sinilah Islam menunjukkan wajah terbaiknya: berilmu, beradab, dan berperan dalam membangun dunia.
Warisan Abu Ja’far al-Mansur melalui Baghdad hidup hingga kini — bukan hanya dalam reruntuhan dan kisah, tetapi dalam semangat peradaban yang terus menginspirasi dunia. Ia membuktikan bahwa peradaban besar lahir dari visi besar, dan bahwa pena dan pikiran dapat membangun kejayaan yang jauh lebih abadi daripada pedang dan perang.