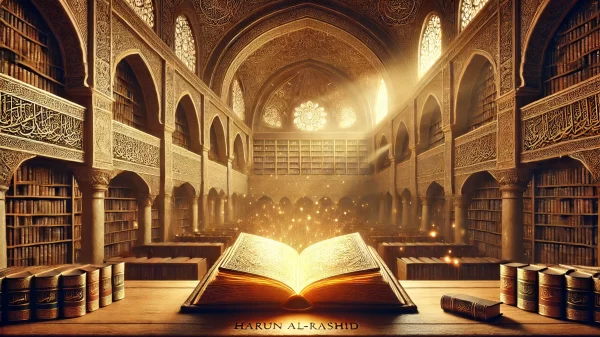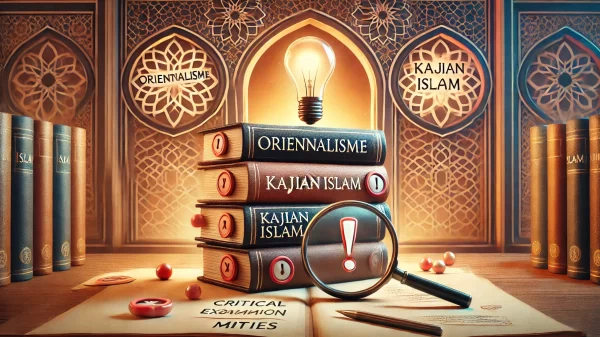Monitorday.com – Dalam lautan luas para ulama hadis klasik, nama Imam Ibnu Hibban menonjol karena keluasan ilmunya, kedalaman analisisnya, dan kecerdasannya dalam menggabungkan hadis, fikih, serta filsafat hikmah dalam satu kerangka ilmiah. Ia dikenal sebagai “ensiklopedis hadis” — seorang ulama yang menguasai banyak bidang sekaligus, namun tetap teguh dalam menjaga keaslian sunnah Nabi ﷺ.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban Al-Busti, lahir di Bustan, Khurasan (Afghanistan modern) sekitar tahun 270 Hijriah (884 M). Ia hidup pada masa setelah Imam Bukhari dan Muslim, di mana ilmu hadis telah berkembang pesat dan menuntut metodologi baru yang lebih sistematis. Sejak muda, Ibnu Hibban menunjukkan kecerdasan luar biasa serta semangat yang tinggi dalam mempelajari ilmu-ilmu agama.
Ia menempuh rihlah ilmiah ke berbagai kota besar Islam — Khurasan, Irak, Syam, Hijaz, dan Mesir — berguru kepada ratusan ulama. Di antara gurunya yang paling terkenal adalah Muhammad bin Ishaq As-Saghani, Ali bin Al-Husain bin Jalal, dan Abu Hatim Ar-Razi. Ia juga belajar langsung kepada ulama-ulama besar yang menjadi murid Imam Bukhari dan Muslim, menjadikannya sebagai penghubung generasi emas ilmu hadis.
Imam Ibnu Hibban memiliki kemampuan luar biasa dalam menghafal hadis. Ia dikenal sebagai hafizh — istilah yang digunakan untuk ulama yang hafal lebih dari 300.000 hadis beserta sanad dan perawinya. Namun, keunggulannya bukan hanya pada hafalan, melainkan juga pada analisis dan metodologi ilmiah.
Karya besarnya yang paling dikenal adalah “Shahih Ibnu Hibban”, kitab hadis yang menjadi salah satu referensi utama setelah Kutubus Sittah. Kitab ini memiliki struktur yang unik — tidak disusun berdasarkan bab fikih seperti Sunan atau Musnad, tetapi berdasarkan tema makna dan maksud hadis. Inilah yang membuatnya disebut sebagai “ensiklopedia hadis pertama dalam Islam.”
Imam Ibnu Hibban tidak hanya meriwayatkan hadis, tapi juga menjelaskan kandungannya dengan hikmah dan penalaran mendalam. Ia memadukan kekuatan dalil dengan pemahaman rasional tanpa keluar dari batas-batas syariat. Pendekatannya ini menjadikan kitabnya hidup, relevan, dan penuh nilai moral.
Selain Shahih-nya, ia juga menulis banyak karya lain seperti:
Al-Majruhin (tentang para perawi yang lemah dan cacat dalam sanad)
At-Tsiqat (tentang para perawi yang terpercaya)
Rawdhatul ‘Uqala’ wa Nuzhatul Fudhala’ (tentang akhlak, hikmah, dan kebijaksanaan hidup)
Ad-Du’afa wa Al-Matrukin (tentang perawi yang tertolak)
Dari karya-karya itu, terlihat betapa Ibnu Hibban bukan hanya ahli hadis, tapi juga seorang psikolog dan pemikir moral. Ia menulis dengan hati, berusaha agar ilmu yang ia tulis tidak hanya mengisi akal, tapi juga menyentuh jiwa.
Dalam Rawdhatul ‘Uqala’, ia menulis kalimat yang masih relevan hingga kini:
> “Ilmu tanpa akhlak akan menjadi kebinasaan, dan akhlak tanpa ilmu akan menjadi kebodohan.”
Ucapan itu menunjukkan keseimbangan hidup yang ia perjuangkan — menjadikan ilmu sebagai jalan menuju kebijaksanaan, bukan sekadar kehebatan.
Imam Ibnu Hibban wafat sekitar tahun 354 Hijriah (965 M) di Bustan, setelah menghabiskan hidupnya menulis, mengajar, dan menjaga hadis Nabi ﷺ dari kesalahan dan penyimpangan.
Warisan intelektualnya membuatnya disebut oleh para ulama sebagai “Imam besar hadis yang selevel dengan Bukhari dan Muslim dalam ketelitian sanad.” Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut bahwa Shahih Ibnu Hibban adalah kitab yang “penuh dengan mutiara makna dan kedalaman hikmah.”
Dari Imam Ibnu Hibban, kita belajar bahwa ilmu yang sejati bukan hanya tentang teks dan hafalan, tetapi juga tentang kebijaksanaan dan akhlak. Ia menunjukkan bahwa seorang ulama sejati bukan hanya penjaga hadis, tetapi juga penjaga hati manusia.