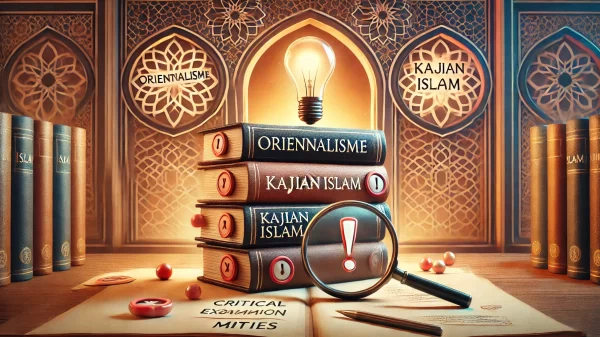RuangSujud.com – Dalam pusaran zaman yang terus berputar, konsep-konsep kehidupan bermasyarakat kerap kali menuntut kita untuk merenung dan meninjau kembali dari sudut pandang yang lebih mendalam. Salah satu istilah yang kini mengemuka dengan segala kompleksitasnya adalah ‘minoritas’. Sekilas, kata ini mungkin terdengar sederhana, merujuk pada kelompok kecil di tengah mayoritas. Namun, bagi umat Muslim, apalagi saat menelusuri khazanah ilmu politik Islam, makna dan implikasinya jauh melampaui batas pandangan sekilas, menyeru kita untuk memahami keadilan dan hikmah Ilahi dalam berinteraksi dengan sesama.
Patut kita pahami, akar kata ‘minoritas’ sendiri bukanlah bagian dari warisan peradaban Islam yang gemilang. Istilah ini baru muncul pada Abad Pertengahan, sekitar abad ke-15 Masehi, dan berkembang di masyarakat Barat. Sejarah mencatat, ketika Islam berjaya, tidak ada istilah khusus yang digunakan untuk mengklasifikasikan pemeluk agama lain yang hidup di bawah naungan daulah Islamiyah. Islam memiliki terminologi yang lebih luhur: ‘ahludz dzimmah’. Mereka adalah non-Muslim yang hidup dengan jaminan perlindungan dan perjanjian dari Allah, Rasul-Nya, serta seluruh kaum Muslimin, menikmati hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara yang aman dan sejahtera.
Penggunaan kata ‘minoritas’ secara implisit seringkali membawa nuansa dominasi mayoritas, yang rentan memicu perlakuan diskriminatif, protes, bahkan ketidakstabilan politik. Apalagi setelah keruntuhan khilafah Utsmaniyah, konsep ini seolah dipaksakan bersamaan dengan pemahaman hak asasi manusia Barat yang kerap ambigu. Kondisi pasca-kolonialisme dan melemahnya hegemoni Islam turut memperumit persoalan ‘ahludz dzimmah’, sebab kini umat Islam pun banyak yang hidup sebagai kelompok mayoritas atau minoritas di berbagai negara, sehingga memerlukan peninjauan ulang terhadap konsep-konsep fiqh klasik seperti dar al-Islam atau dar al-harb.
Inilah saatnya bagi umat untuk berani melakukan ijtihad baru yang fleksibel dan bijaksana. Kita bisa berkaca pada langkah Pakistan pada tahun 1949, yang setelah kajian mendalam, memutuskan untuk meniadakan kewajiban membayar jizyah bagi non-Muslim. Langkah ini bukan tanpa alasan, melainkan demi menciptakan keseimbangan dan menghindari potensi perlakuan serupa yang keras terhadap kaum Muslimin di negara-negara non-Muslim. Ironisnya, di saat yang sama, komitmen Barat untuk menghormati kebijakan negara-negara Islam terhadap kelompok non-Muslim seringkali tidak sejalan, bahkan terjadi intervensi berlebihan yang menunjukkan inkonsistensi terhadap konsep ‘minoritas’ itu sendiri. Islam mengajarkan hak yang bertanggung jawab, bukan kebebasan mutlak tanpa batas syariat.
Tidak hanya non-Muslim, namun kelompok-kelompok Muslim di luar arus utama juga terkadang dipaksa masuk dalam kategori ‘minoritas’. Padahal, selama mereka masih bersyahadat dan berpegang pada Islam, mereka adalah bagian dari umat. Ulama besar seperti Imam Abd al-Qahir al-Jurjani dan Imam al-Khatib al-Baghdadi memang menggariskan tentang sekte ekstrem yang dapat dikategorikan sesat, namun Imam as-Syathibi menawarkan kebijaksanaan: jangan terburu-buru menghukumi hanya karena perbedaan fiqh. Sikap bijak, merujuk pada substansi syariat (maqashid syariah), jauh lebih bermanfaat daripada sanksi yang berpotensi memicu intervensi asing dan mengancam stabilitas umat. Negara memiliki peran penting dalam membimbing akidah dengan pemahaman yang benar akan kemuliaan Islam.
Oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan untuk terus menggali dan merumuskan format fikih yang ideal bagi keberagaman kelompok dalam masyarakat Islam kontemporer. Mari kita dengan berani dan cerdas menghadapi diskursus ‘minoritas’ yang menjadi salah satu topik sentral tatanan dunia baru ini. Dengan berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah, serta semangat ijtihad yang selaras dengan maqashid syariah, semoga kita mampu menghadirkan keadilan, kedamaian, dan keberkahan bagi seluruh penghuni bumi, sebagaimana teladan agung yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Insya Allah!