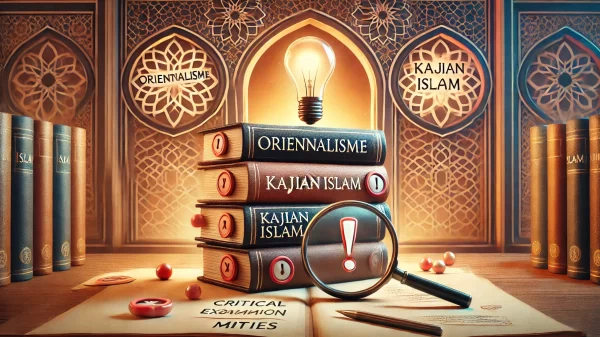Monitorday.com – Musa al-Hadi bin Al-Mahdi adalah khalifah keempat Dinasti Abbasiyah, yang memerintah dalam waktu singkat — hanya sekitar satu tahun, dari 169 hingga 170 H (785–786 M). Meski singkat, masa kekuasaannya penuh warna dan menjadi bab penting dalam sejarah Abbasiyah, karena memperlihatkan transisi dari kepemimpinan penuh kasih ayahnya, Al-Mahdi, menuju masa pemerintahan yang lebih tegas dan militeristik. Sosok al-Hadi dikenal sebagai pemimpin muda yang kuat, ambisius, dan berjiwa pemberani, meski akhirnya terbentur oleh kerasnya politik istana.
Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Musa bin Muhammad al-Mahdi, lahir sekitar tahun 144 H (761 M). Sejak kecil, ia tumbuh di istana Baghdad dan mendapat pendidikan politik langsung dari ayahnya. Sebagai putra sulung Al-Mahdi, ia disiapkan untuk menjadi penerus tahta kekhalifahan. Maka, ketika Al-Mahdi wafat secara mendadak di wilayah Persia pada tahun 169 H, Musa yang saat itu berusia sekitar 24 tahun, naik sebagai khalifah menggantikan ayahnya.
Begitu naik tahta, al-Hadi menunjukkan kepribadian yang berbeda jauh dari ayahnya. Jika Al-Mahdi dikenal lembut dan dermawan, maka al-Hadi lebih keras dan pragmatis. Ia bertekad menegakkan disiplin, memperkuat kontrol pusat, dan menertibkan pejabat yang dianggap lemah atau korup. Dalam pidato pertamanya, ia menegaskan:
> “Negara ini akan tegak hanya dengan tangan yang kuat dan hukum yang ditegakkan.”
Salah satu langkah pertamanya adalah menata ulang struktur militer dan pemerintahan. Ia memperbesar gaji pasukan dan memperketat loyalitas prajurit terhadap khalifah. Ia juga menempatkan orang-orang muda yang dinilai tangguh di posisi strategis, menggantikan pejabat tua peninggalan masa Al-Mahdi. Meski langkah ini menimbulkan ketegangan politik, ia yakin kekuasaan yang kuat hanya bisa dijaga dengan disiplin.
Al-Hadi juga dikenal memiliki gaya kepemimpinan langsung. Ia sering memimpin pasukan sendiri dalam operasi militer, memeriksa laporan gubernur tanpa perantara, bahkan turun ke medan latihan militer di luar Baghdad. Ia berusaha menampilkan diri sebagai sosok khalifah pejuang, bukan penguasa istana. Langkah ini membuatnya disukai oleh kalangan militer, tapi sebagian pejabat sipil dan ulama menilai gaya ini terlalu keras.
Namun, pemerintahan al-Hadi tidak lepas dari gejolak politik internal. Salah satunya adalah ketegangan dengan keluarganya sendiri — terutama ibunya, Al-Khayzuran, yang sangat berpengaruh sejak masa Al-Mahdi. Al-Khayzuran dikenal sebagai perempuan cerdas dan bijak yang sering ikut campur dalam urusan pemerintahan. Al-Hadi yang berjiwa independen menolak campur tangan ibunya dan berusaha membatasi peran politik perempuan di istana.
Konflik antara ibu dan anak ini menjadi legenda tersendiri dalam sejarah Abbasiyah. Dalam beberapa catatan, Al-Khayzuran berusaha menasihati putranya agar memerintah dengan kasih dan mendengarkan para penasihat. Namun al-Hadi menjawab tegas, “Kekuasaan tidak bisa dibagi, Ibu. Aku adalah khalifah, bukan anak kecil.” Ketegangan ini semakin meningkat hingga akhirnya memengaruhi stabilitas politik istana.
Selain persoalan keluarga, al-Hadi juga harus menghadapi pemberontakan politik. Beberapa kelompok Alawiyin (keturunan Ali bin Abi Thalib) yang kecewa karena janji politik Abbasiyah belum terpenuhi, kembali bangkit di Hijaz. Pemberontakan yang paling besar terjadi di wilayah Madinah, dipimpin oleh Husain bin Ali, dikenal sebagai “Syahid Fakhkh”. Al-Hadi mengirim pasukan untuk memadamkannya, dan perlawanan itu berhasil dihancurkan dengan cepat. Namun, darah yang tertumpah di tanah suci itu meninggalkan luka mendalam dalam hubungan Abbasiyah dengan keturunan Nabi ﷺ.
Dalam bidang ekonomi, al-Hadi melanjutkan kebijakan ayahnya dalam memperkuat perdagangan dan pertanian, namun dengan pendekatan yang lebih administratif. Ia menertibkan sistem pajak, menekan korupsi di kalangan gubernur, dan memastikan kas negara tidak disalahgunakan. Namun karena waktunya singkat, dampak kebijakan ini belum sempat terasa luas.
Al-Hadi juga dikenal cerdas dalam berbicara dan fasih dalam bahasa Arab klasik. Ia sering berdiskusi dengan para ulama dan penyair, meskipun sikapnya terhadap para ahli agama kadang keras. Ia menolak penggunaan agama untuk kepentingan politik, dan lebih memilih pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Meski begitu, ia tetap menjaga pelaksanaan syariat di masyarakat dan memerangi aliran sesat.
Sayangnya, pemerintahannya berakhir tragis dan terlalu cepat. Setelah hanya sekitar setahun memimpin, al-Hadi wafat secara mendadak pada tahun 170 H (786 M) di daerah Isabadh, dekat Baghdad. Sebagian sumber menyebut ia meninggal karena sakit mendadak, namun ada pula riwayat yang menyebut bahwa kematiannya berkaitan dengan konflik internal istana — bahkan ada dugaan bahwa ibunya, Al-Khayzuran, terlibat karena ketegangan politik yang tak terselesaikan. Kebenarannya masih menjadi perdebatan sejarah.
Meski masa kekuasaannya singkat, Musa al-Hadi meninggalkan warisan penting: ketegasan dan semangat kepemimpinan yang berani. Ia menegakkan kembali otoritas khalifah dan menunjukkan bahwa kekuasaan tidak boleh menjadi alat kompromi bagi kepentingan pribadi. Ia mungkin keras, tapi di balik sikapnya, ada niat tulus untuk menjaga kekuatan negara.
Sejarawan menyebutnya sebagai khalifah muda yang “mati sebelum waktunya.” Namun, dari semangat dan visi yang ia tunjukkan, lahir generasi baru kepemimpinan Abbasiyah — termasuk adiknya, Harun ar-Rasyid, yang kelak membawa kekhalifahan menuju puncak kejayaan.
Musa al-Hadi adalah pengingat bahwa bahkan masa singkat pun bisa meninggalkan jejak besar, jika dijalani dengan tekad dan keberanian. Ia bukan khalifah sempurna, tapi ia adalah potret pemimpin muda yang berani berdiri sendiri di tengah badai kekuasaan.