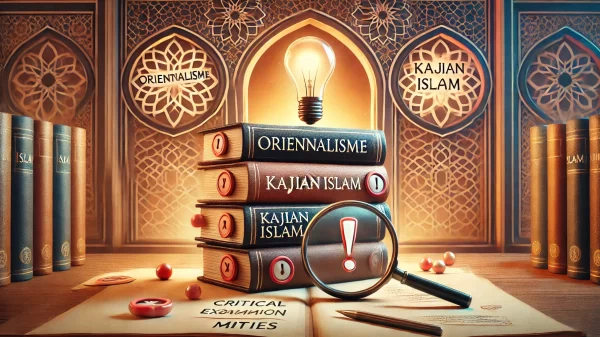Monitorday.com – Khalifah Al-Mahdi bin Abu Ja’far al-Mansur (memerintah 158–169 H / 775–785 M) meninggalkan jejak sejarah yang kuat sebagai pemimpin bijak yang memadukan kemakmuran, ilmu, dan moralitas dalam satu kesatuan kepemimpinan. Jika ayahnya, Abu Ja’far al-Mansur, adalah pembangun struktur kekuasaan dan fondasi negara, maka Al-Mahdi adalah pengisi ruh peradaban itu — menjadikannya lembut, berjiwa sosial, dan penuh kebajikan. Di tangannya, kekhalifahan Abbasiyah berubah dari sistem yang kuat menjadi peradaban yang hidup dan manusiawi.
Warisan terbesar Al-Mahdi adalah pemimpinannya yang berkarakter welas asih dan adil. Ia dikenal dekat dengan rakyat, bahkan sering turun langsung ke pasar Baghdad untuk mendengar keluhan masyarakat. Banyak kisah mencatat bagaimana ia berjalan malam hari tanpa pengawal, memeriksa harga, dan menegur pejabat yang menzalimi rakyat kecil. Sikap ini menumbuhkan rasa cinta dan hormat di hati rakyat, menjadikan kekhalifahan tidak hanya ditakuti karena kekuasaannya, tetapi juga dihormati karena keadilannya.
Ia memahami bahwa pemerintahan Islam tidak bisa hanya bertumpu pada hukum dan pedang, tetapi harus berlandaskan kasih dan keadilan. Dalam satu khutbahnya yang terkenal, ia berkata:
> “Kekuasaan tanpa rahmat adalah kehancuran, dan keadilan tanpa kasih adalah kesia-siaan.”
Karena itu, seluruh kebijakannya selalu menyeimbangkan antara kekuatan dan kelembutan. Ia menegakkan hukum dengan tegas, tetapi memberi ruang ampun bagi yang mau bertaubat. Ia memperkuat militer, namun menghindari peperangan yang tidak perlu. Ia menghukum koruptor, tetapi menolong rakyat miskin dengan kemurahan hati yang luar biasa.
Warisan kedua adalah penguatan ilmu dan budaya Islam. Al-Mahdi melanjutkan kebijakan ayahnya dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, namun dengan sentuhan yang lebih spiritual. Ia memuliakan para ulama, mendukung kegiatan penerjemahan buku-buku asing, dan menjadikan Baghdad sebagai rumah bagi ilmu dari seluruh dunia.
Pada masa pemerintahannya, karya-karya ilmuwan Persia dan Yunani mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ia menugaskan para ahli untuk mempelajari ilmu astronomi, kedokteran, dan matematika, tetapi juga memastikan agar semua ilmu tetap sejalan dengan aqidah Islam. Ia percaya bahwa ilmu dan iman tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Di bawahnya, lahir generasi ulama yang bukan hanya ahli agama, tetapi juga cendekiawan dunia.
Al-Mahdi juga berperan penting dalam menumbuhkan budaya literasi dan sastra. Istana Abbasiyah pada masanya menjadi tempat berkumpulnya penyair, penulis, dan sejarawan. Karya-karya mereka tidak hanya berisi pujian kepada khalifah, tetapi juga refleksi moral dan sosial yang memperkaya kehidupan intelektual masyarakat. Dari masa inilah tradisi penulisan sejarah, seperti karya Tarikh al-Tabari dan Kitab al-Aghani, mulai mendapat tempat di dunia Islam.
Warisan ketiga Al-Mahdi adalah pembangunan moral dan sosial masyarakat. Ia memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik — melarang praktik riba, menertibkan pasar, dan memperketat pengawasan terhadap moral pejabat. Ia juga memperluas sistem zakat dan sedekah negara. Banyak rumah sakit (bimaristan), panti anak yatim, dan rumah singgah dibangun atas perintahnya. Ia percaya bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari kemegahan istana, tetapi dari senyum rakyat di jalanan.
Kedermawanannya terkenal di seluruh dunia Islam. Ia sering menghapus pajak bagi petani miskin dan membagikan harta pribadi untuk membantu yang membutuhkan. Dalam salah satu riwayat, ia pernah berkata kepada bendahara istana,
> “Jika engkau ragu kepada siapa harta ini harus diberikan, berikanlah kepada yang lapar. Karena Allah tidak akan menanyakan mengapa aku memberi, tetapi akan menanyakan mengapa aku menahan.”
Selain itu, Al-Mahdi juga meninggalkan warisan penting dalam bidang pemerintahan dan stabilitas dinasti. Ia memperkuat sistem administrasi negara dan memastikan suksesi kekuasaan berjalan tertib. Ia menunjuk putranya, Musa al-Hadi, sebagai putra mahkota, dan setelahnya Harun ar-Rasyid — keputusan yang menunjukkan pandangannya yang jauh ke depan dalam menjaga keberlanjutan kekhalifahan. Dengan cara itu, Dinasti Abbasiyah terhindar dari konflik perebutan kekuasaan yang sering menimpa dinasti lain.
Warisan Al-Mahdi juga terletak pada penciptaan iklim spiritual yang damai. Ia berhasil menyeimbangkan antara kebebasan berpikir dan kesetiaan pada syariat. Masyarakatnya boleh berdebat tentang filsafat dan ilmu, tetapi tidak melampaui batas iman. Ia membangun tatanan yang membuat rakyat hidup dalam harmoni antara dunia dan akhirat.
Ketika wafat di Masabadhan pada tahun 169 H (785 M), Al-Mahdi meninggalkan dunia Islam dalam keadaan stabil, makmur, dan bersemangat. Rakyat menangisinya, bukan karena kehilangan penguasa, tetapi karena kehilangan seorang ayah. Sejarawan al-Tabari mencatat bahwa tidak ada pemberontakan besar selama masa pemerintahannya — bukti bahwa keadilan dan kasihnya telah menenangkan seluruh negeri.
Warisan Al-Mahdi menjadi landasan spiritual dan sosial bagi generasi setelahnya. Dari nilai-nilai yang ia tanam, lahir masa paling gemilang dalam sejarah Islam — masa Harun ar-Rasyid, putranya, yang membawa Abbasiyah ke puncak kejayaan peradaban. Semua itu tidak akan mungkin tanpa pondasi moral dan kemakmuran yang diwariskan oleh Al-Mahdi.
Dalam catatan sejarah, nama Al-Mahdi berarti “yang mendapat petunjuk.” Dan memang demikianlah ia hidup — seorang pemimpin yang memerintah dengan petunjuk Allah, memadukan ilmu dengan iman, dan kekuasaan dengan kasih. Ia membuktikan bahwa peradaban Islam bukan dibangun oleh besi dan pedang, melainkan oleh kebajikan dan keadilan yang menyentuh hati manusia.